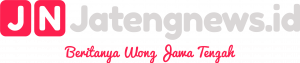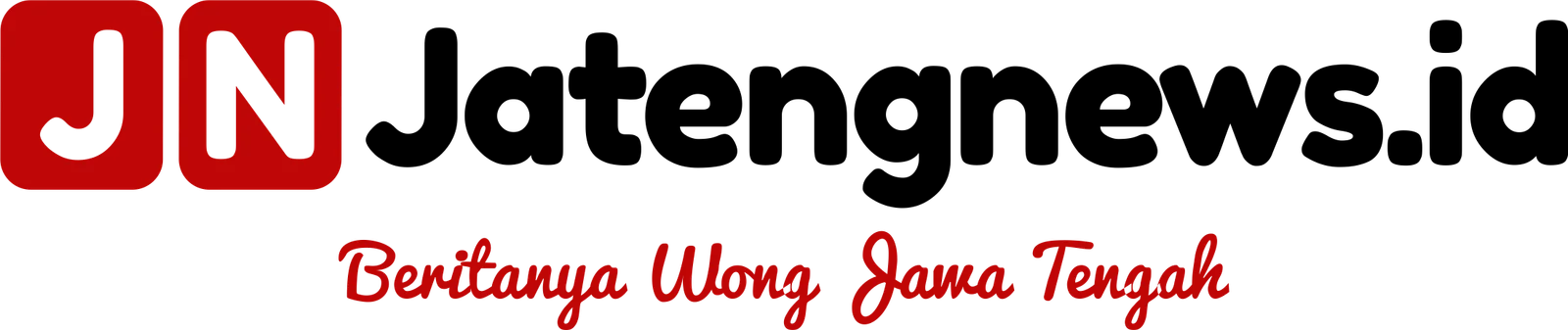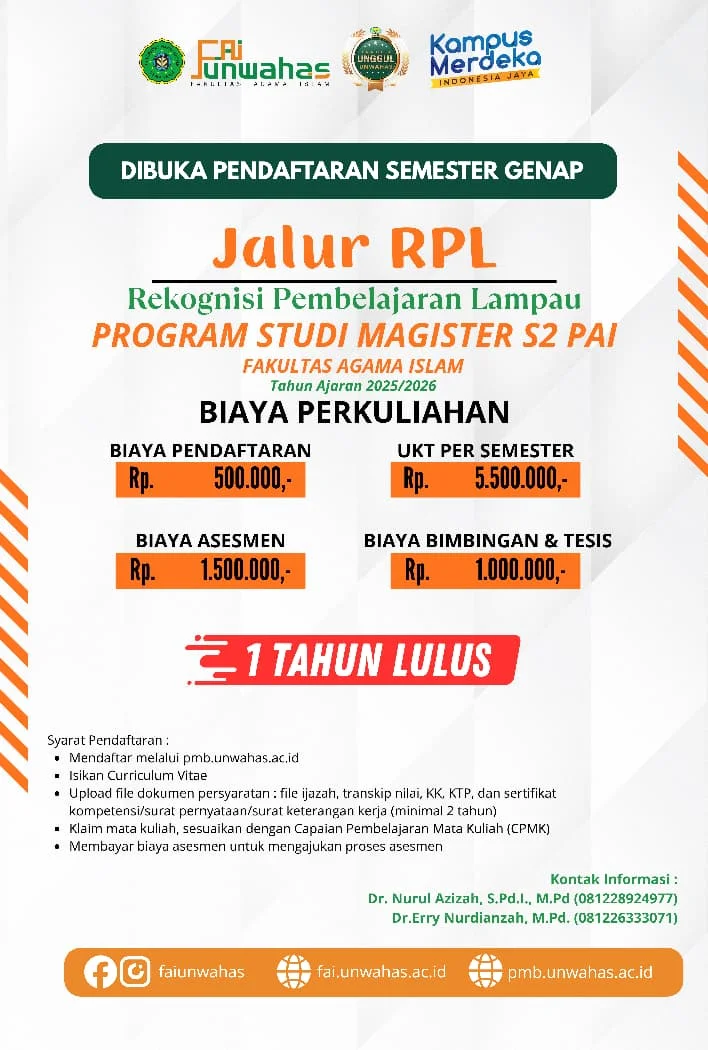Penulis : Eko Widianto, Dosen Bahasa Indonesia UIN Walisongo Semarang, Mahasiswa PhD di University of Galway, Irlandia
Semarang, Jatengnews.id – Setiap hari, masyarakat terus dijejali berita-berita kontroversial atas pernyataan para pejabat publik. Mulai dari “semua tanah milik negara”, hingga “guru adalah beban negara”.
Seolah-olah, satu pernyataan belum sempat terklarifikasi, muncul kembali pernyataan lain yang bikin geleng-geleng kepala. Mengapa frasa yang ringan diucapkan ini menjadi luas dampaknya? Apakah memang bahasa yang sering dikatakan ‘omon-omon’ sepenting itu? Ataukah, setiap orang wajib belajar bahasa sepanjang masa?
Dalam konteks penggunaan bahasa di masyarakat, khususnya pada dimensi pemerintahan, kita tentu ingat teori ‘praktik diskursif’ yang dikenalkan oleh linguis kenamaan Norman Fairclough.
Menurutnya, bahasa dapat dilihat melalui tiga tahap praktik diskursi, yakni produksi, distribusi, dan konsumsi. Bahasa menjadi amat vital posisinya jika dilihat dari siapa yang menciptakannya, bagaimana cara menyebarluaskannya, dan seperti apa orang lain meresepsinya.
Sayangnya, frasa-frasa sederhana di atas diucapkan oleh pejabat publik, yang mana mereka adalah publik figure, orang yang selalu menjadi sorotan setiap gerak lakunya. Risiko menjadi figur publik adalah anomali-anomali yang muncul akan amat mudah ditangkap oleh audiens.
Sebaliknya, hal yang lumrah dan biasa saja tidak akan begitu diperhatikan. Oleh karena itu, setiap capaian prestasi yang mereka lakukan tidak begitu digubris oleh masyarakat. Sementara blunder yang hanya dibuat sekali, bisa menjadi bola panas yang menarik diperbincangkan. Inilah mengapa para pejabat publik tidak bisa sembarangan ‘omon-omon’ atau memproduksi bahasa sesuka hati.
Karena setiap pejabat publik memiliki daya tarik, setiap hasil produksi bahasanya akan menjadi komoditas yang ‘mahal’. Frasa seperti ‘setiap tanah milik negara’ atau ‘guru adalah beban negara’ merupakan produk yang siap diolah dengan bumbu segala rupa. Pada tahap distribusi teks, peran media massa menjadi esensial. Bahasa ini dapat diolah, dicitrakan, dan didistribusikan kepada khalayak umum sebagai komoditas. Untuk menjadikannya lebih renyah, media massa amat mafhum.
Hal ini sudah lama dibicarakan oleh Chomsky melalui Manufacturing Consent-nya yang berpandangan bahwa media bukan sekadar penyampai fakta, tetapi “pabrik wacana” yang menjadikan setiap berita menjadi komoditas.
Bahasa yang sudah difabrikasi tersebut menjadi santapan masyarakat secara serampangan.
Dalam proses konsumsi ini, setiap kepala berhak menciptakan interpretasi masing-masing berdasarkan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, hingga preferensi politik. Dengan demikian, penyataan yang sudah tersebar luas tersebut dipastikan menimbulkan gejolak pro dan kontra. Pada tahap ini, bahasa memainkan perannya untuk mengaduk-aduk emosi dan kesadaran para audiensnya.
Ia mengaktifkan alarm pemikiran kritis, yang salah satunya adalah “assesment alarm”. Setiap orang akan dengan mudah menciptakan standar penilaian terhadap produsen bahasa tersebut, yang dalam hal ini adalah para pejabat publik.
Tren permohonan maaf
Ada sebuah tren komunikasi yang dipakai oleh para figur publik saat ini, khususnya para pejabat. Mereka akan dengan mudah memunculkan pernyataan yang kontroversial. Setelah pernyataan tersebut didistribusikan dan dikonsumsi, lalu memunculkan dinamika serta polemik, mereka tidak akan ambil pusing. Langkah yang akan diambil adalah sebatas muncul kembali ke publik, menyampaikan klarifikasi, dan permohonan maaf.
Seolah-olah, kata maaf akan menyelesaikan segalanya. Polemik yang terjadi akan hilang ditelan berita-berita lain yang barangkali lebih kontroversial lagi. Padahal, sejatinya polemik itu tidak pernah usai. Ia hanya menjadi gundukan sampah yang menggunung di kemudian hari.
Perlu digarisbawahi bahwa bahasa merupakan cerminan isi kepala manusia. Sebelum diproduksi, bahasa merupakan preposisi-preposisi yang ada di benak manusia. Dia berwujud ide, yang amat lama mengendap dan direnungkan berwaktu-waktu, sebelum pada akhirnya diutarakan menggunakan alat ucap menjadi ujaran.
Oleh sebab itu, setiap ujaran yang diucapkan oleh seseorang, bukan semata-mata kalimat nirmakna. Ujaran tersebut merupakan cerminan langsung gagasan, pikiran, dan ide yang mengisi ruang kepala penuturnya.
Lantas, bagaimana jika bahasa itu dimanipulasi? Dalam ilmu retorika, bahasa menjadi alat yang amat artifisial. Ia dapat dimodifikasi, bahkan dimanipulasi. Seseorang dapat membuat gagasan yang buruk menjadi cenderung lebih indah dan berterima.
Tentu kita ingat istilah “dirumahkan” untuk para pekerja yang menjadi korban PHK. Kita juga pasti familier dengan kata “diamankan” untuk para koruptor yang terkena OTT. Namun, dalam konteks pernyataan para pejabat publik di atas, bahasa ini diproduksi secara spontan dan natural. Kedua aspek ini menggambarkan apa yang secara lahiriah mengendap di dalam pikiran penuturnya. Oleh karena itu, bahasa ini justru lahir secara murni, tidak dibuat-buat, dan apa adanya.
Pentingnya belajar bahasa
Agaknya, bahasa menjadi mata pelajaran atau jurusan kuliah yang tidak terlalu populer. Namun, berkaca pada fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, sepertinya belajar bahasa terus relevan hingga kini. Bahasa bukan sekadar pelajaran teoretis, tetapi lebih dari sekadar praktik berkomunikasi. Bahasa dapat menjadi alat kuasa. Bagi para pejabat publik, bahasa dapat digunakan sebagai alat untuk meraih simpati, atau menjadi bumerang pendulang kontroversi. Kedudukannya menjadi fatal dan vital agar mereka lebih berhati-hati dalam memunculkan statement di hadapan publik.
Sementara itu, bagi masyarakat belajar bahasa juga memainkan peran penting dalam konteks edukasi. Dengan kemampuan bahasa yang memadai, kita dapat memahami, mencerna, dan menilai setiap pernyataan pejabat publik. Kita dapat mengkritisi secara komprehensif isi kepala mereka melalui pernyataan-pernyataan yang muncul. Melalui bahasa, kita juga disadarkan bahwa setiap komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah bukan sebatas ‘omon-omon’ belaka, melainkan cerminan pekerjaan mereka. (03)